“Aku shalat, tetapi aku tidak tahu apalagi yang aku ingat darinya…
Aku shalat dhuha, delapan rakaat atau dua.”
–Qays bin Al Muluh
Saya tidak tahu, dan tidak cukup rajin untuk mencari tahu, apakah kisah Qays itu benar-benar ada dan mahsyur akibat penuturan dari mulut ke mulut selama ribuan tahun, atau hanya bermula dari karya sastra yang mendunia, sehingga orang-orang secara tak sadar menerimanya sebagai kisah nyata. Digubah dengan judul Laila dan Majnun oleh salah seorang penyair Persia abad kedua belas, Nizami Ganjavi, cerita tentang Qays memiliki akhir yang tragis seperti halnya dongeng-dongengan cinta Abelard dan Eloisa dari Perancis, atau Petrarch dan Laura dari Italia, atau Romeo dan Juliet dari Inggris.
Qays, pemuda gagah bermata jernih, lahir dari orang tua yang terpandang. Ia dihormati semua orang, diharapkan segenap perempuan. Sampai pada sebuah titik di hidupnya, Qays bertemu dengan seorang perempuan. Ia pun jatuh kagum kepadanya, kepada kecantikannya, kepada urai rambutnya yang hitam seperti malam–yang karenanya sang perempuan dinamai Laila.
Rasa kagum tersebut meluruhkan Qays, mensenyawakan tatapan-tatapan renjana yang kebetulan disambut oleh Laila. Ditatapinya juga Qays dengan tersipu, sorot mata perempuan yang jatuh cinta.
Namun, apa mau dikata, orang tua Laila tak tahan dengan gunjingan orang-orang tentang anak perempuannya. “Bisa-bisanya seorang gadis terhormat,” ujar para tetangga, “saling mengasihi dengan lelaki tanpa berbekal ikatan apa-apa.”
Bersama rasa malu, orang tuanya kemudian membawa Laila ke negeri jauh. Diam-diam menghindar pergi dari Qays dan semesta merah mudanya. Meninggalkan Qays dalam ketidaktahuan. Kesedihan. Kesengsaraan. Ketertolakan. Sehingga ia meratapi apa saja dan menghubungkan apa saja dengan Laila.
“Demi Allah wahai biawak padang pasir, katakanlah padaku.
Apakah Laila bagian dari kalian atau Laila seorang anak manusia?”
Dendangnya ketika melakukan thawaf di tanah haram.
“Ya Allah tabahkanlah kecintaanku yang mendalam pada Laila.
Aku mencintai Laila dan Laila mencintaiku.
Demikian pula ontanya menyukai ontaku.”
Ungkap Qays pada ayahnya.
“Demi Allah, cintaku pada Laila tulus, jiwaku selalu merindu, pikiranku selalu mengenang, dan lidahku tak pernah kelu menyebut namanya. Laila laksana minuman yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga kalbuku. Cintaku pada Laila adalah cinta suci, tidak tercampur dengan nafsu walau sebutir debu. Meskipun orang-orang mencela kami, mengusir, dan menyia-nyiakan diriku.”
Kemudian, orang-orang pun menjuluki Qays sebagai Majnun Laila, orang yang gila pada Laila. Orang yang menjadi gila karena Laila. Dan nahas, sampai akhir hayatnya, mereka pun tidak pernah bersama.
***
Ke mana kekaguman Laila dan Majnun bermuara?
Nizami mengakhiri kisahnya dengan memperkenalkan kita pada seorang pemuda bernama Zayd. Zayd dikabarkan memimpikan Majnun dan Laila setelah kematian keduanya. Zayd menceritakan bahwa pada akhirnya, Qays dan Laila dapat bergandeng mesra di atas singgasana surga. “Permadani surga terhampar di dekat sungai kecil yang mengalir di bawah singgasana itu,” tulis Nizami, “dilengkapi dengan hidangan nikmat dan cahaya berkilauan,” tutupnya.
Akhir kisah tersebut begitu manis–siapa yang tak ingin kepahitan-kepahitan hidup kita di dunia berlabuh pada kebahagiaan abadi di surga? Walaupun sejatinya, akhir kisah tersebut kontradiktif dengan hikmah-hikmah yang Islam perkenalkan kepada kita.
Saya pun lebih memilih untuk kembali melihat dari mana tulisan ini berpijak. Bahwa saya tidak tahu apakah segala tentang Laila dan Majnun ini benar-benar ada, sekadar rekaan manusia, atau hibrida dari keduanya.
Pendapat Buya Hamka rasanya lebih rasional mengenai ini; bahwa Laila dan Majnun tak lebih hanya kisah dari tanah Arab, yang latarnya membentang dari Hijjaz menuju Gaza, yang jalan ceritanya menyertakan padang rumput, gurun pasir, dan suku-suku penggembala. Tak lebih.
Di sisi lain, Islam justru mengenalkan kita pada kisah tentang Pemuda-Qais dengan versi yang sama sekali berbeda. Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais, begitu orang-orang biasa menjuluki sang pemuda. Siapa nama sesungguhnya, tidak disebutkan dalam literatur yang saya baca.
Hadits mengenai Muhajir Ummu Qais terletak pada urutan pertama hadits arba’in. Seolah-olah ingin menyampaikan bahwa substansi hadits tersebut menjelaskan pondasi, pijakan, dan titik tolak utama dari segala apa yang kita kerjakan: niat.
Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Rasa kagum sang pemuda kepada perempuan yang dijuluki Ummu Qais sebenarnya ditujukan untuk bersauh dalam bingkai pernikahan. Namun dalam menuju ke sana, perjalanan sang pemuda tersandung kerikil-kerikil keikhlasan. Sang pemuda merasa harus memakai tabir “hijrah”, menyembunyikan niatnya, sesuatu yang harusnya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya.
Muhajir Ummu Qais “hanya” terpeleset dalam niat. Menjadikan perbuatannya tak sinkron dengan niatnya. Dan Rasulullah lantas menegurnya. Lalu, akan bagaimana nasib kekaguman yang tersandung dalam segenap niat, seluruh perbuatan, hingga sesemburat tujuannya? Sebagaimana pun indah retorika-retorika kekaguman yang membungkus perasaan Qays bin Al Muluh, seharusnya kita tahu, kisah Laila dan Majnun tak memuarakan kita dalam kesimpulan apa-apa.
***
Stephen R. Covey dalam buku sejuta umatnya, 7 Habbits of Highly Effective People, merumuskan sebuah kebiasaan yang dapat kita pakai dalam menyikapi sergapan rasa kagum: begin with the end in mind. Mulailah mensketsa-sketsa segala sesuatunya dari tujuan akhir. Mulailah mengambil keputusan untuk lanjut melangkah atau berhenti, dengan memvisualisasikan di mana pelabuhan yang kita tuju. Ke mana akhirnya. Muaranya.
Seandainya yang datang kepada Majnun di tubir kewarasannya adalah Covey, dan bukannya dua teman bodoh yang memberikan ide kepada Majnun agar menyamar menjadi perempuan sehingga bisa mengendap masuk ke kamar Laila (dan dituruti), akhir kisah Majnun mungkin bisa lebih manusiawi.
Seandainya Laila tak begitu saja membalas tatapan Majnun, dan lebih memilih berkata, “Sudahkah kamu bertanya-tanya, ke mana rasa kagummu kepadaku akan membawa kita dan dirimu sendiri? Sebagaimana aku selalu menanyakan ke mana rasa kagumku kepadamu akan membawa kita dan diriku sendiri?” Mungkin keduanya akan lebih bisa berpikir jernih tentang tujuan mereka. Termasuk apa yang harus diperjuangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan mungkin Qays akan lebih mampu mengambil keputusan sejantan Ali.
Tetapi, ketika jawabannya adalah “tidak ke mana-mana”, maka mereka harus paham bahwa rasa kagum tersebut sudah tidak perlu dituruti.
Dan kepahaman mungkin akan membawa Laila merasionalkan segala keterpanaannya, menjinakkan semesta ketersipuannya. Mengingatkan diri sendiri bahwa Allah tahu apa yang paling tersembunyi, Allah mengawasi. Dan mungkin seraya membalas tatapan Qays dengan perkataan setegas, sejernih angkasa, “Rasa kagummu tak perlu diutarakan karena kita tidak berkapasitas untuk saling mengutarakan kekaguman.”
Ibnu Khaldun berkata bahwa sejarah bergerak dalam bentuk spiral, berulang. Dan kita, manusia di punggung bumi ini, mungkin saja terjatuh dalam sebuah pengulangan peristiwa yang semirip kisah Laila dan Majnun.
Maka, sebelum jatuh kepada kegilaan dan kompleksitas hingga lupa bilangan rakaat dalam shalat-shalat kita, kita harus sigap untuk melaksanakan petuah Covey: begin with the end in mind. Dan ketika kita tidak melihat muara apa pun, jika kita merasa bahwa kita tidak akan dibawa ke mana pun, maka kita harus segera menerjemahkan, bahwa kekaguman yang kita miliki, atau orang lain miliki, seluruhnya, tidak akan membawa kita ke mana-mana.
Tidak akan mengantarkan kita ke mana-mana. Kecuali, mungkin, pada kemudharatan.
Maka berhenti. Jika semuanya adalah dimensi ketidakjelasan, maka berhenti.
Jangan masuk lebih jauh.
Agar hidup kita lebih efektif dan tidak akan sia-sia dengan kerepotan-kerepotan perasaan.
Berjalanlah lurus, sampai waktu yang tepat, hingga kita dapat memperjuangkan kekaguman kita…
…dalam kejelasan muara.
“Cinta itu adalah perasaan yang baik dengan kebaikan tujuan jika tujuannya adalah menikah.”
Prof. Abdul Halim Abu Syuqqah.
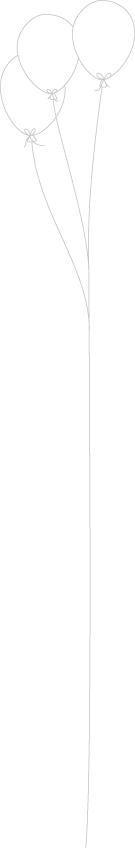
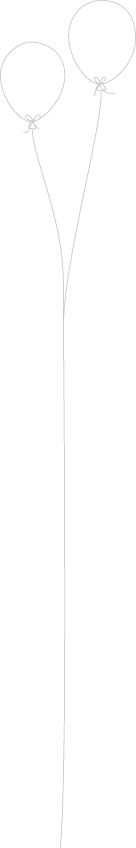
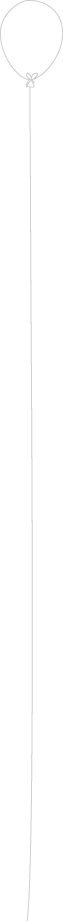
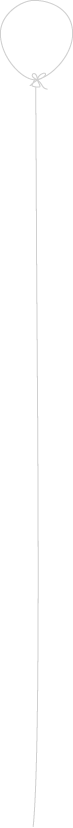
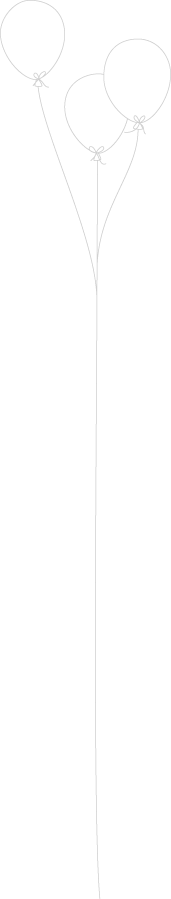
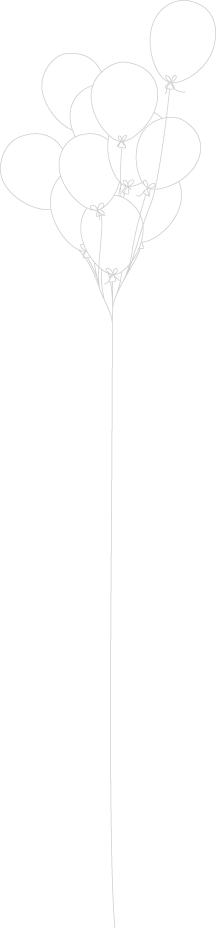
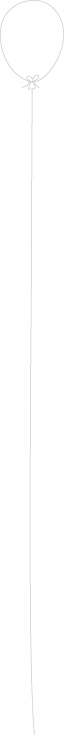
Aaaaakkk jatuh cinta sama seluruh tulisan kiki!
Sebagaimana aku juga jatuh cinta sama tulisan Erliiin! Ikut seneng aja gitu bawaannya kalau baca 😀
Ada satu ide tulisan yang muncul gara-gara tulisanmu lho, lupa yang ke mana, tapi yang tentang “menjual kemiskinan”. Semoga cepat direalisasikan. Terimakici sudah berkunjung Erl! *hug*